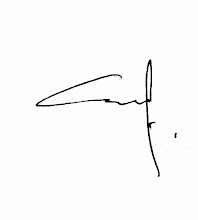Rumah cahaya
Rumah itu kecil
Tapi begitu besar untuk dimakna
Catnya kusam mengelupas
Namun cahayanya begitu terang
Atap-atapnya pun tak pantas untuk di kata
Tapi tetap saja ia mampu menghadirkan sejuta asa dan tawa
Orang di dalamnya hanyalah orang biasa
Namun punya mimpi mulia yang menyentuh moksa lewat tiap goresan pena
Momen Ta’aruf di Rumah Cahaya
(Ta’aruf Itu Bernama Toleransi)
Oleh : Cipta Arief Wibawa
Minggu pagi yang cerah. Seorang pemuda dengan agak tergesa melaju kencang memecah jalan raya dengan sepeda motornya. Sesekali Ia melirik jam di sebelah kanan tangannya. Sejurus kemudian Ia lewat sebuah jembatan dan belok ke sebelah kiri melewati TPU tua yang hidup berdampingan dengan sebuah mesjid. Ah, sungguh angker tempat ini, begitu batinnya sambil terus menambah laju sepeda motornya. Beberapa menit kemudian Ia berhenti tepat di depan sebuah rumah yang tidak bisa dibilang tua, namun sudah terlihat cukup usang. Pandangannya mematung sesaat mengamati rumah yang pasti akan segera jadi bagian hidupnya ini.
“Maaf, Dek anggota FLP juga ya?” Sebuah suara membuyarkan sang pemuda dari rotasi lamunannya. Ternyata seorang lelaki setengah baya yang tengah bertanya padanya.
“Ia, Pak. Ini memang rumahnya.”
“Kalau begitu adik anggota FLP juga, kan? Kenalkan nama saya Hardo.”
“Betul, Pak. Saya memang anggota FLP. Nama saya…”
Belum lagi selesai sang pemuda memperkenalkan namanya dari dalam rumah sudah terdengar panggilan untuk segera masuk. Akhirnya, tanpa pikir panjang mereka berdua segera menuju ke dalam rumah tersebut.
Suasana santai dan menenangkan menyelimuti seisi rumah saat Bang Fadhly yang tak lain adalah Ketua Umum FLP mulai membuka pembicaraan. Di dalam rumah ada begitu banyak orang. Sebagian besarnya adalah anggota-anggota baru (Forum Lingkar Pena) FLP Sumut. Sang pemuda sendiri—yang juga termasuk dalam jejeran anggota baru—dengan kagum dan takhzim terus mendengarkan setiap potong kata yang keluar dari bibir Bang Fadhly itu. Sesekali ia mengangguk-angguk, entah karena setuju dengan sebuah kalimat atau mungkin terkagum-kagum.
Entahlah. Satu saja yang pasti, Ia bahagia.
“Sebentar lagi kita akan memulai sebuah permainan,” Kata Bang Fadhly sambil membetulkan posisi duduknya, “Jadi harap bersiap-siap dulu ya. Yang mau ambil nafas silahkan diambil nafasnya.” Kontan saja, semua orang tertawa mendengar lelucon ringan tersebut.
Bersamaan dengan itu, sebuah kertas yang berjudulkan daftar absensi terus digilir. Pemuda itu baru saja selesai membubuhkan tanda tangan tepat di kolom namanya “Cipta Arief Wibawa”.
Pak Hardo yang sedari tadi duduk di sebelah sang pemuda lantas berkata, “Oh, jadi namanya Cipta, ya?”
“Eh…, iya Pak. Nama saya Cipta. Maaf ya Pak tadi nggak sempat ngenalin nama dulu karena keburu disuruh masuk.”
Kata sang pemuda dengan cepat sambil menatap kolom absen tempat Pak Hardo membubuhkan tanda tangan. Sang pemuda itu agak terkejut melihat nama yang tertera di absen itu. “Sihardo Belinyu”. Dalam hati ia terus mengingat sesuatu yang terasa tak asing terkait nama itu.
Pemuda itu diam tapi otaknya masih lincah meliuk-mengingat setiap sudut memori yang terhampar di dalam kepalanya .
“Wah…, teman-teman. Pak Hardo ini orang yang luar biasa,” Bang Fadhly menatap ke arah Pak Hardo, “Seperti yang teman-teman ketahui, FLP itu adalah sebuah organisasi yang membuka diri untuk siapa saja. Artinya, semua kalangan berhak untuk masuk. Azas Flp yang berdasarkan pada keislaman, keorganisasian, serta kepenulisan itu harus dimaknai secara universal.”
Semua orang mengangguk. Mungkin berpikir bahwa Bang Fadhly secara tersirat ingin mengatakan bahwa orang seusia seperti Pak Hardo tidak akan jadi masalah jika mau untuk terus belajar. Tapi sang pemuda berpikir lain. Ia yakin maksud Bang Fadhly berkata begitu tidak hanya sekedar menyinggung masalah usia saja. Pasti ada hal lain, katanya dalam hati.
“Ayo segera ambil posisi duduk yang nyaman. Permainan kita mulai sekarang…” Bertepatan dengan perintah bermain dari Bang Fadhly, pemuda itu pun telah ingat tentang perihal nama Pak Hardo dan kata-kata Bang Fadhly yang sejak tadi menjadi puzzle di kepalanya.
Kota Bangka. Tidak salah lagi, kalau firasatku benar, Gua Maria, itu salah satu tempat tujuan wisata yang menarik bagi banyak orang, begitu batinnya dalam hati.
Permainan terus berlangsung. Mulai dari permainan mengingat setiap nama peserta hingga permainan menirukan jenis-jenis binatang satwa. Pemuda itu dengan senyum mengembang terus mengikuti jalannya acara. Bagaimanapun juga, tujuan dari permainan ini adalah untuk lebih mendekatkan tiap anggota baru yang umumnya masih merasa asing. Dalam psikologi sendiri, tujuan dilakukannya hal seperti ini adalah untuk menghindari Pluralistic Ignorance, bahasa sederhananya agar para anggota baru mengerti tentang bagaimana FLP itu sendiri dan juga norma-norma yang ada di dalamnya.
Suasana saat itu jelas ramai karena dibungkus dalam rinai keakraban. Penghujung acara pun tiba. Seorang pengurus FLP meminta agar para anggota baru berembuk untuk memilih seorang ketua kelas yang akan meng-koordinir seluruh angkatan. Tugasnya mulai dari penginfoan hingga menentukan siapa setiap minggunya yang akan ber-tilawah dan memberi sedikit tausiyah.
Tiba-tiba seorang peserta meneriakkan nama Pak Hardo dan langsung disambut riuh-setuju oleh hampir seluruh orang yang hadir dalam rumah itu. Sang pemuda terkejut. Ia juga melihat ekspresi yang tak jauh berbeda tergurat dalam tiap sudut wajah Pak Hardo. Jelas sekali keringat Pak Hardo deras bercucuran. Pasti Pak Hardo merasa sungkan dan tidak enak. Bagaimana bisa dia mengkoordinirtilawah dan tausiyah untuk teman-teman. Ini pasti akan jadi masalah baginya, begitu pikir sang pemuda. Dengan lemah Pak Hardo menatap ke arah pemuda tersebut. Pemuda itu pun dengan cepat mengangguk seolah merasa Pak Hardo tengah berbicara dengannya.
Ia lantas berpikir cepat. Bagaimanapun juga Ia harus mendapatkan solusi agar Pak Hardo tidak dipilih menjadi ketua, namun syaratnya semua orang harus setuju dan tidak menentang argumen yang diberikannya. Aha, pemuda itu tersenyum. Ia lantas mengacungkan tangan.
“Teman-teman, Saya rasa dalam memilih seorang ketua tidak baik langsung asal menunjuk saja tanpa memperhatikan dengan lebih jauh siapa yang ditunjuk,” Sang pemuda menghela nafas sebentar lalu melanjutkan, “Sebagaimana yang kita ketahui, Pak Hardo itu berbeda dengan kita semua yang rata-rata masih menyandang status sebagai mahasiswa, Dia sudah bekerja. Pasti ada lebih banyak persoalan yang harus ia selesaikan dibandingkan dengan kita yang masih mahasiswa…”
Seorang peserta lain mengacungkan tangan dan menyela sang pemuda, “Maaf saudara Cipta. Saya rasa untuk masalah koordinir angkatan bukanlah hal yang sulit. Kita hanya perlu seminggu sekali saja mengkoordinir angkatan kita. Jadi saya pikir ini bukanlah hal yan berat untuk siapa saja termasuk Pak Hardo.”
Para peserta lain ikut mengamini kata-kata peserta itu. Sang Pemuda hanya tersenyum. Dalam hati ia berkata, yes, kena!
“Maaf, kalau masalah berat atau tidak, Saya rasa bukan kita yang menentukan, namun orangnya langsung yang lebih tahu. Mungkin lebih baik kita tanyakan saja pendapat dari Pak Hardo.”
Pak Hardo pun lantas berbicara dan menyatakan ketidaksediaannya menjadi ketua kelas. Akhirnya diputuskan bahwa calon lain yang jadi ketua kelas untuk anggota baru FLP saat ini.
Dalam hati sang pemuda bersyukur seraya menasehati dirinya sendiri. Bagaimanapun perbedaan harus disikapi dengan kepekaan dan kebijakan. Belum tentu apa yang kita rasa baik akan baik juga bagi orang lain. Kuncinya adalah empati dan toleransi. Ah... Hidup ini luar biasa, ujar pemuda itu dalam benak hatinya.
Ramainya Ta’aruf Di Rumah CAHAYA
(Episode Hidup Si Pengukir Sejarah)